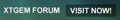“He… kalian mau ke mana?” suaranya menandakan sedang mabuk parah.
“Dengar, kami tidak akan membuat keributan di sini.
Kami hanya ingin pergi dari sini, oke?” Sekali ini kutegakkan tubuhku dan bicara dengan sangat tegas.
“Jadi… menyingkirlah!”
Kurasa jika memang diharuskan, diriku sudah bertekad akan melakukan apapun demi kebebasan kami berdua. Aku sudah tak peduli lagi jika harus menjadi seorang pembunuh, atau menjadi mayat sekalipun. Aku tak sudi menjadi pecundang.
“Apa kamu bilang, perempuan tolol? Memangnya siapa dirimu itu, hah?” tangannya yang bebas meng gapai-gapai di udara,tubuhnya semakin limbung.Bagus, keadaannya menambah keberanian dalam dadaku!
“Aku, putri seorang pejuang’ 45, bangsa Indonesia!”
sergahku lantang. Dengan sisa-sisa kesadaran yang masih dimilikinya, telunjuknya menuding-nuding wajahku.
“Jij ben niks waard en je heb niks geen pass-port en geen tiket, dus godverdomme wegwezen juiiie!” (“Kamu tidak punya apa-apa, tidak berarti apa-apa, tidak punya paspor dan tiket, jadi pergilah kamu dari sini!”) Ya Tuhan, sungguhkah ini? Ternyata begini mudahkah kami terlepas dari cengkeramannya? Mengapa tidak dari kemarin-kemarin aku melakukannya? Mengapa ketakutan akan kehilangan nyawa anakku begitu menghancurkan setiap hasrat bangkang dalam diriku? Demikian aku sempat menjeritkan kenaifanku. Ah, sudahlah, sudahlah, jerit hatiku kemudian. Akhirnya, Tuhanku, Tuhanku, terima kasih!
Bagaikan sinting rasanya diriku mencekal kuat-kuat tangan anakku. Setengah berlari kuseret langkah kami berdua, bergegas pergi. Kami tak membawa apapun selain yang melekat di tubuh dan paspor, ditambah beberapa lembar gulden yang kutemukan di laci dapur. Aku tak memikirkan apapun lagi. Bagiku yang terpenting pergi sejauh mungkin. Samar-samar suaranya masih terdengar meracau tak jelas.
–o0o–
Udara dingin di penghujung bulan Juli pada dini-hari itu seketika menyergap tubuh kami. Beberapa saat kupangku anakku dan kudekap erat tubuhnya yang gemetar. Selang kemudian anakku minta diturunkan, tentu merasa kasihan kepadaku yang terhu yung-huyung limbung.
Kami berjalan kaki menuju stasiun terdekat selama kurang lebih 20 menit. Tak ada pejalan kaki lainnya kecuali kami berdua. Aku berjuang keras menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk di bagian bawah tubuhku. Kuyakinkan pada diriku bahwa rasa sakit badaniah itu sungguh bukan apa-apa, jika dibandingkan dengan kebebasan yang baru kami dapatkan.
“Mama… sakit ya?” anakku merandek, lalu menengadahkan wajahnya, sepasang bintang mencari-cari jawaban di wajahku.
“Tidak apa-apa, Nak… Mama baik-baik saja,” sahutku seraya membelai pipi-pipinya yang putih.
Masih kuat berjalan, Sayang?”
“Ya, Mama… aku sudah kuat, kuat sekali!” dia tersenyum manis dengan selaksa bintang yang berbi nar-binar di matanya. Itulah bintang asa dan citaku!
“Kita lanjutkan perjalanan, Cinta?” tanyaku seraya menahan gelombang keharuan yang bagai me nggumpal-gumpal di leher, di tenggorokan, di dada terus menusuk ke persendian tulang, ke sekujur jiwa dan ragaku.
“Siaaap!” jawab anakku bersemangat sekali, walau kutahu itu hanya demi menghibur hatiku. Kami pun terus berjalan, tanpa berkata-kata lagi.Aku telah memelajari peta yang sempat kuambil begitu menginjakkan kaki di bandara Schiphol. Tujuan yang terlintas di benakku adalah Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag. Aku membeli tiket kereta api senilai 25 gulden (saat itu mata uang Belanda gulden) dari Hilversurn ke Utrecht.
Beberapa saat kurasai aura keheningan, kesenyapan yang ajaib membalut diriku. Anakku merebahkan kepalanya di atas pangkuanku,sesaat kemudian dia telah tertidur lelap.
Napasnya mengalun lembut melalui hidungnya.
Mencermati tubuhnya yang mungil dan kurus, tak tahan air mataku berderaian yang segera kuhapus, khawatir mengusik tidurnya. Kurasa inilah saat tidurnya yang terlena sejak meninggalkan Tanah Air.
Beberapa jenak kubiarkan pula diriku menikmati udara kebebasan, walaupun masih ada kekhawatiran si jahanam memburu kami. Sewaktu kereta api berhenti di stasiun Utrecht, aku tak membangunkan anakku melainkan menggendongnya pelan-pelan. Se mangat hidupku serasa mengalir deras, tatkala merasai detak jantung anakku yang menyatu dengan detak jantungku sendiri.
“Ya, kita harus bertahan hidup, Anakku… Harus, haruuus!” desisku berulang kali, tak terhitung lagi sebagai upaya menguatkan benteng pertahanan diri yang baru kuraih.
Di sebuah bangku panjang di sudut stasiun Ut-recht, kubiarkan waktu berjalan dengan semestinya. Penampilan kami pasti aneh di mata mereka, tidak sesuai dengan musim. Aku mengenakan celana jins, kaos dalam yang dirangkap baju hangat. Anakku masih mengenakan piyama dirangkap celana jins dan jaketnya. Tak kupedulikan orang-orang yang melintas di hadapan kami, sekilas memandangiku ter heran-heran. Hari, apa peduliku?
Sebaliknya aku yang harus heran. Mengapa tiada seorang pun yang meluangkan waktunya, sekadar menanyakan keadaan karni? Bukankah kami tampak sangat menyedihkan, wajahku amat pucat dengan bilur kebiruan di pipi dan keningku? Sosok mungil dalam pangkuanku tampak mengerut kecil, diliputi ketakberdayaan dan keringkihan. Mengapa kalian tak peduli?
Di sinilah di daratan Eropa kami kini berada. Di negeri sebuah bangsa yang konon sangat menjunjung tinggi kesopanan, peradaban luhur,di mana para nyonya begitu senang menata rumah, dan menyediakan makanan yang lezat untuk keluarganya. Di mana salah seorang warganya begitu kejam memerlakukan kami berdua, tak punya hati, tak punya nurani, hanya nafsu iblis yang menjelma utuh dalam dirinya…
Ops, ternyata ada juga yang mau memerhatikan keberadaan kami. Seorang gadis muda menghampiri kami, membungkuk di samping anakku, kemudian memandangi wajah anakku lekat-lekat. Aku menyapanya dan mencoba berkomunikasi. Aku mengatakan bahwa kami baru datang dari luar kota, bermaksud pergi ke Den Haag.
“Anda harus melanjutkan perjalanan dengan kereta lagi, Mevrouw,” berkata gadis yang kutaksir mahasiswa atau karyawati itu.
“Dia ini… apakah anak Anda?” selidiknya.
“Iya, dia anakku, mengapa?” balik aku bertanya.
“Mmm, kasihan… tidak apa-apakah dia?” tanyanya pula dengan sorot mata ingin tahu, kemudian sejenak lebih mencermati keadaan anakku. Aku berusaha tersenyum.
“Tidak, Sister, dia hanya kelelahan.”
Gadis itu menatap wajahku dan tersenyum simpati.
Entah apa yang ada dalam pikirannya, saat kemudian ia mengingatkanku agar berhati-hati. Ia juga mengatakan ingin membantuku, tapi menyesal sekali karena sudah ada janji. Ia berpamitan dengan ramah, setelah minta izinku untuk mengelus pipi anakku, dan meletakkan sekotak cokelat di dekat tangan anakku.
Kupandangi tas punggungnya sambil kuhela napas dalam-dalam.
Setidaknya pengetahuanku bertambah, pengharapanku membernas tentang peradaban bangsa ini.
Gadis itu, siapapun dia, telah membuat hatiku terharu.
Sikapnya terhadap anakku sungguh telah menggoyah benteng kebencian dan dendam dalam dadaku. Ya, tidak semua warga Belanda seperti si Gez!
Dan tiba-tiba benakku disergap berbagai macam pikiran.
Kesadaran itu, kesadaran akan segala keputusan dengan sebab akibatnya itu… Menggugatku!
“Kita mau ke mana lagi, Mama?” Pada saat bersamaan anakku terbangun, agaknya bisa menangkap kebimbanganku. Kubiarkan dia menikmati cokelatnya sebagai pengulur waktu. Aku memang tak bisa langsung menyahut, kugigiti ujung-ujung bibirku.